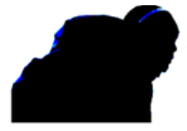Semarang, 11 Oktober 2019.
Malam itu — sekitar jam setengah 7 malam — saya, Jo dan Mas Halim sedang duduk di sebuah meja di depan booth tahu gimbal di Semawis. Jo, sang tuan rumah, mengajak saya dan Mas Halim ke sini untuk mencari makan. Sewamis sendiri merupakan sebuah tempat makan bertema street food yang berada Kawasan Pecinan. Sekitar satu atau dua kilo meter dari Kota Lama. Saya dan Mas Halim mampir ke Semarang untuk transit, menunggu jadwal kereta Joglosemarkerto yang baru akan berangkat jam 21.58. Kami baru saja melakukan perjalanan dari Lasem, Rembang.
Secara random, obrolan kami bertiga tiba-tiba sampai kepada sosok Opa. Beliau adalah seorang warga asli Lasem. Saat awal-awal Lasem mulai dikenal oleh para pejalan dan fotografer, banyak pemandu yang membawa tamu ke rumah Opa. Menurut cerita Mas Halim dan Jo, Opa adalah sosok yang cukup welcome kepada para turis yang ingin mencari tahu sejarah atau apapun yang berkaitan dengan Lasem, meskipun beliau – tentu saja – tidak mengenal turis yang bersangkutan. Masih menurut kedua teman saya itu, ada setumpuk majalah kuno di salah satu meja di rumah Opa. Katanya, saat kita membuka halaman salah satu majalah – secara random – halaman itu adalah perwujudan diri kita di masa depan. Tentu saja saya tak percaya. Ya kali masa depan ditentukan oleh halaman majalah.
Ketika menceritakan tentang sosok Opa dan suasana rumahnya, Mas Halim juga bilang bahwa Lasem itu unik. Menurutnya, hanya orang-orang yang benar-benar “terpanggil” saja yang bisa datang ke sana. Maksudnya, hanya mereka yang benar-benar punya niat yang bisa datang ke Lasem. “kayak ibadah haji saja”. Timpal saya.
Mungkin Mas Halim memang ada benarnya. Sebelum akhirnya melakukan perjalanan dengan dia, saya sudah ada niat untuk melakukan perjalanan ke Lasem seorang diri. Tanpa teman, tanpa pemandu. Beberapa hari sebelum berangkat, Mas Halim tiba-tiba menghubungi melalui WhatsApp bahwa ia ingin gabung. Dia mendapat kabar bahwa saya akan Lasem dari si Jo ketika mereka berdua bertemu di Semarang beberapa hari sebelum Mas Halim menghubungi saya. Pada akhirnya, justru Mas Halim lah yang repot mengurus persiapan perjalanan. Dia yang mencari penginapan sekaligus persewaan sepeda di Lasem. Juga menentukan destinasi-destinasi yang akan kami kunjungi. Belakangan, barulah saya sadar bahwa melakukan perjalanan ke Lasem tanpa pemandu akan menjadi sangat merepotkan karna Lasem bukanlah destinasi wisata sembarangan. Sebelum melakukan perjalanan dengan saya, Mas Halim sudah dua kali mengunjungi Lasem. Kesimpulannya, Mas Halim adalah teman perjalanan sekaligus pemandu :))
Lasem sendiri secara teknis merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jadi bayangkan saja jika saya harus menjelajahi satu kecamatan tanpa tahu dimana saja spot-spot yang menarik. Lasem berada di Jalur Pantura yang menghubungkan Rembang-Tuban.
Lasem banyak dikenal orang sebagai Kawasan Pecinan. Banyak warga Tionghoa yang hidup di Lasem sejak jaman kolonial Belanda hingga sekarang. Tempat saya menginap sendiri (Oemah Ijo dan Roemah Oei) dimiliki oleh keturunan Tionghoa (dari namanya saja sudah kelihatan). Beberapa rumah batik juga dimiliki oleh keturunan Tionghoa. Di sisi lain, orang-orang juga mengenal Lasem sebagai kawasan pondok pesantren. Di Lasem, ada sebuah pondok pesantren yag lokasinya berada di Kompleks Pecinan. Beberapa bangunannya bahkan mengadopsi arsitektur China yang khas dengan warna merahnya itu. Ketika mengunjungi Pantai Caruban (salah satu pantai di Lasem), saya juga melewati sebuah pondok pesantren.
Jadi sebenarnya, Lasem itu bukan Kawasan Pecinan, juga bukan Kawasan Pesantren. Lasem adalah dimana orang-orang dari berbagai etnis hidup bersama dan berdampingan. Saling melengkapi dan berbagi peran. Sama halnya dengan tempat-tempat lain di Indonesia.
Ketika sedang ngopi di sebuah warung kopi (warung, bukan kafe) pada Jum’at pagi, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang dari berbagai etnis hidup membaur menjadi satu di Lasem. Seorang Tionghoa paruh baya sedang menikmati secangkir kopi lelet sambil membahas politik. Lalu tiba-tiba datang seorang lelaki usia 50-an dengan logat Jabodetabek yang sepertinya baru saja mengantar anaknya sekolah. Tanpa casciscus dulu sebagai awalan, si lelaki tiba-tiba ngomongin salah satu tetangganya. Saya yang tak minat dengan topik semacam ini langsung mengalihkan focus ke buntelan ketan di depan mata, sembari nyruput kopis susu yang ampasnya sudah mulai mengendap.
Saya sendiri ke Lasem karna “teracuni” oleh jepretan-jepretan para fotografer yang pernah hunting foto di Lasem. Foto-foto human interest serta bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial Belanda merupakan objek utama di Lasem. Di Lasem, kita bisa memotret aktivitas para pembatik di rumah batik, petani garam di tambak garam, ataupun warga lokal yang kebetulan lewat di sebuah gang di Desa Karangturi. Desa Karangturi sendiri adalah sebuah desa yang menjadi salah satu destinasi utama di Lasem. Di desa inilah kita bisa menyaksikan bangunan-bangunan rumah tua yang sudah ada sejak jaman kolonial. Dengan pintu-pintu vintage-nya yang ikonik.

Di hari kedua kunjungan ke Lasem, Mas Halim mengajak saya ke sebuah bangunan tua bekas stasiun. Ya, Lasem dulu merupakan jalur kereta api. Mas Halim sebenarnya sudah menjelaskan panjang-lebar soal ini kepada saya, tapi saya tak begitu paham. Yang saya tahu, tempat ini kini sudah menjadi tempat parkir truk-truk besar. Dan kebetulan tak jauh dari tempat ini ada sebuah pabrik (pabrik apa ya saya kok lupa). Pabrik ini memanfaatkan area bekas stasiun untuk memarkir truk-truk kontainer pengangkut barang. Ketika kami ke sana, beberapa supir (atau mungkin warga lokal) sedang asik bermain judi.
Mas Halim juga mengajak saya mengunjungi sebuah rumah batik milik seorang pengusaha batik bernama Pak Santoso. Beliau adalah pemilik batik Pusaka Beruang. Sebenarnya, tujuan kami bukanlah rumah batiknya, melainkan pohon trembesi (?). Kami awalnya tak berniat untuk masuk rumah batik milik Pak Santoso ini.
Supaya tidak penasaran, lihatlah foto di bawah ini.

Foto di atas adalah pohon trembesi besar yang kebetulan lokasinya berada persis di depan rumah batik yang memproduksi batik Pusaka Beruang milik Pak Santoso. Saat kami sedang berteduh sembari foto-foto di bawah pohon ini, sang tuan rumah tiba-tiba keluar bersama rombongan tamu dari Kompas. Salah satu orang Kompas yang menjadi tamu Pak Santoso — Namanya Silvi — adalah teman Mas Halim. Jadilah Mas Halim punya perantara untuk bicara dengan Pak Santoso. Endingnya, kami (atau lebih tepatnya Mas Halim wkwk), meminta ijin untuk masuk ke rumah menyaksikan para pengrajin batik. Tentu saja saya tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memotret aktivitas para pembatik.
…
Sragen, 19 Oktober 2019
Saat menulis postingan ini, saya sedang duduk di beranda rumah. Hujan baru saja turun. Ini adalah hujan pertama setelah kemarau yang panjang tahun ini. Aroma tanah basah begitu menyegarkan di indra cium, merasuk hingga ke dalam dada. Seandainya aroma tanah basah ini bisa dimasukkan ke dalam botol, saya akan menjadikannya parfum dan mengirimnya ke rumahmu. Ya, saya sedang mengutip lirik lagu Adhitia Sofyan. Ape lo!
Sudah seminggu sejak kunjungan saya ke Lasem. Bayangan suasananya masih sangat terasa. Lasem memang panas, tapi saya tak kapok datang ke sana. Ketika sudah tua dan punyak anak-anak nanti, Lasem mungkin akan menjadi salah satu tempat dimana saya akan mengajak mereka menikmati sunset di tambak garam atau sekedar makan Lontong Tuyuhan di desa Tuyuhan sembari berkata “waktu muda dulu ayah pernah sepedaan keliling Lasem, nak. Waktu itu ayah harus mampir Indomaret dulu untuk beli singlet. Panas”
PS
Beberapa hasil hunting foto di Lasem kemaren sudah saya upload ke Unsplash dan Pexels. Silakan dipakai kalau memang butuh untuk keperluan apapun.