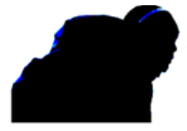“Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” -Mark Twain.
Beberapa waktu belakangan ini saya sering merenungkan nasihat penulis asal Amerika itu. Mungkin benar bahwa suatu saat nanti kita akan lebih menyesali apa-apa yang tidak kita lakukan daripada sesuatu yang telah kita lakukan. Ada begitu banyak contoh orang-orang yang sudah kepala 4 ke atas yang menyesali kehidupan yang mereka jalani tersebab tidak memperjuangkan apa yang menjadi impian mereka di masa muda dulu. Mereka hidup tapi tidak dengan hidupnya. Di masa depan, saya sangat tidak ingin memiliki jenis kehidupan yang seperti itu. Hidup yang terjebak dalam sistem industri yang kalau kata Bondan Prakoso & Fade2Black di salah satu lagunya, SOS, memiliki pola: Lahir, sekolah, bekerja, mati.
Mendaki gunung adalah salah satu cara yang saya tempuh untuk menhindari penyesalan seperti apa yang dikatakan Mark Twain. Sejujurnya, mendaki gunung adalah bagian dari jalan hidup yang saya rencanakan. Sebuah grand design kehidupan yang saat ini cuma saya dan Tuhan yang tahu.
Lempuyangan, 11 September 2018 pukul 07.29 WIB
Pagi itu saya sedang menunggu kereta Prameks jurusan Jogja-Solo. Saya hendak pulang ke Solo setelah menumpang tidur di kos teman malam sebelumnya. Senin, 10 September 2018 saya baru saja turun dari Gunung Sumbing.
Perjalanan ke Gunung Sumbing adalah sebuah perjalanan yang tak terduga sekaligus tak terencana. Awalnya, kami berencana mendaki Gunung Argopuro di Jawa Timur, namun jalur pendakian sedang ditutup karna rawan kebakaran. Puncak musim kemarau begini memang rawan terjadi kebakaran di gunung.
Jika Gunung Slamet adalah atapnya Jawa Tengah, maka Gunung Sumbing adalah balkonnya. Gunung ini adalah gunung tertinggi nomor dua di Jawa Tengah.
Orang-orang yang suka mendaki gunung itu mungkin adalah orang-orang paling naif sedunia. Sudah tahu bakal capek tapi tetap dilakukan. Tapi, apa bedanya dengan masyarakat urban Jakarta yang sering ngeluh macet tapi tetap naik kendaraan pribadi? Atau orang-orang yang bilang “sudah ganti presiden tapi hidup gini-gini aja” padahal mereka memang tak pernah berbuat lebih untuk hidupnya?

Hidup ini memang kompleks karna setiap kepala punya pemikiran yang tak sama. Tujuan dan cara orang menjalani kehidupan tak akan pernah sama. Jadi, berhentilah menjadi komentator atas hidup orang lain.
Pendakian Gunung Sumbing kemaren adalah tentang angin dan track kejam dari base camp ke Pos 1 dan Pos 3 ke Pos 4. Kedua track itu adalah track yang paling membuat saya banyak ber-istighfar. Kami butuh waktu sembilan jam dari base camp Butuh, Kaliangkrik ke Pos 4, tempat kami nge-camp.
Walau lelah dan pegal, tak ada pendakian yang tak menyenangkan. Begitupun dengan pendakian ke Gunung Sumbing. Juga banyak sekali pelajaran hidup yang bisa dipetik. Waktu perjalanan naik, kami berpapasan dengan banyak penduduk lokal — terutama ibu-ibu — yang menggendong kayu bakar yang bobotnya bisa mencapai 50 kg. Juga hasil-hasil ladang. Dengan track yang sedemikian menyiksa bagi saya sebagai pendaki, apa yang dilakukan mereka adalah sebuah pertunjukan tentang perjuangan hidup dan menjadi pesan tak terucap untuk “selalu ada alasan untuk bersyukur”.
Saya sempat bertanya kepada salah satu ibu yang membawa kayu bakar.
“Pados saking pundi, buk?” Nyari dimana, buk?.
“Nginggil Pos 2 mriku, mas” atas pos dua situ, mas.
Untuk informasi, kami membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam sewaktu perjalanan naik dari basecamp ke Pos 2. Kondisi track dari base camp Butuh ke Pos 2 ini naik terus. Tanpa track datar sama sekali.
Angin adalah musuh terbesar saat mendaki Gunung Sumbing. Kami benar-benar dibuat kewalahan oleh angin yang bertiup cukup sepanjang perjalanan naik-turun. Mendirikan tenda menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali dilakukan. Angin juga turut membawa debu-debu di Pos 4 masuk ke tenda-tenda kami. Saking kencangnya angin dan banyaknya debu yang masuk ke tenda, kami tak bisa memasak nasi untuk mengisi energi sebagai bekal turun. Kami baru bisa memasak nasi di pos 2, setelah melakukan perjalanan sekitar 3,5 jam. Tadinya, kami mau sok keren dengan makan di base campa saja. Tapi fisik memang tak bisa bohong. Kaki kami sudah gemetar tak beraturan.
Puncak tak pernah menjadi obsesi utama saya ketika mendaki gunung walaupun saya akan tetap berusaha untuk mencapainya. Alhamdulilah, untuk kesekian kalinya, pagi itu saya bisa berdiri di tanahNya yang tinggi, Puncak Sejati, Gunung Sumbing.
Gunung Sumbing. Terima kasih untuk anginmu, untuk track berbatumu, untuk track tanahmu, untuk puncakmu, untuk sunrisemu, untuk langitmu, untuk mataharimu, untuk debumu, untuk rumputmu, untuk tanjakanmu, untuk sungai-sungaimu yang kering serta untuk segala pelajaran yang telah kau berikan tanpa pernah kau ucapkan. Juga terima kasih untuk Rifqy, Eko dan Mas Rendra atas pendakian yang tak biasa ini.
Diketik di Stasiun Lempuyangan, Jogja sambil menunggu kereta.